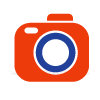Napas seni pertunjukan adalah penonton. Sorak sorai penonton menjadi bagian puncak keberhasilan dari suatu pertunjukan seperti dangdut, campur sari, tayub, wayang kulit, jaranan, reog, dan ludruk. Penonton hadir sebagai upaya menyatukan jiwa dengan sajian yang dilihatnya. Ada ekstase, semacam trans, bahwa di depan panggung pertunjukan, penonton menjadi dirinya yang bebas, meluapkan segala kegundahan hati lewat nyanyian dan teriakan.
Gelaran pertunjukan adalah ekosistem yang tidak melulu mendasarkan episentrum estetika dari apa yang tersaji di atas panggung, tapi juga pada suara gemuruh di selingkarnya. Sebagaimana bising mainan anak-anak, penjual makanan, dan tukang parkir yang hidup melekat pada pementasan-pementasan kesenian tradisi di negeri ini.
Semua menjadi pikat bahwa pertunjukan laksana momentum menggerakkan roda perekonomian masyarakat arus bawah serta ruang sosialisasi untuk bertemu, menyapa dan berkomunikasi. Sebuah peristiwa yang langka, bahkan jauh sebelum adanya pandemi, kita telah menjadi soliter, dengan dunia yang semakin menciut menjadi layar-layar digital.
Masih Terbata-Bata
Kita menduga pandemi akan mengakhiri eksistensi tubuh penonton seni pertunjukan. Saat pemerintah menggaungkan gerakan hidup anyar bertajuk new normal di tengah situasi pandemi, semua mulai bergerak dan berbenah. Mal-mal mulai membuka diri dengan berbagai ketentuan yang ketat, pariwisata kembali dihidupkan sebagai bagian dari bisnis perpelancongan, gedung-gedung bioskop diatur tempat duduknya agar penonton tak berdekatan, sekolah hendak mengakhiri musim libur, dan masih banyak lagi.
Dalam situasi yang demikian, kalangan masyarakat seni pertunjukan masih terbata-bata dalam melakukan formulasi ideal menghadapi hidup berdalih kenormalan baru.
Padahal, menciptakan tata kelola baru berkesenian menjadi sebuah keniscayaan jika ingin terus hidup dan bertahan. Sayangnya, hingga kini tidak ada role model yang dapat diacu sebagai pijakan agar daya hidup seni pertunjukan masih berdetak di musim pandemi.
Pemerintah lewat Direktorat Jendral Kebudayaan maupun dinas-dinas kebudayaan di tiap daerah (provinsi-kota-kabupaten) masih belum menginisiasi mencetuskan blue print tata cara, metode, dan teknis pemanggungan seni pertunjukan, baik untuk menghadapi hidup new normal maupun sesudah pandemi berakhir.
Gairah membawa gerbong seni pertunjukan dalam format digital hanya ramai di awal, namun terasa jemu kemudian. Pertunjukan daring di masa pandemi memang menjadi marak, dan memang itu alternatif paling memungkinkan, tetapi alih-alih menciptakan satu genre baru gaya pemanggungan, yang terjadi justru terjebak pada urusan-urusan di luar kesenian.
Pertunjukan virtual ditonton seringkali tidak berhubungan dengan kualitas karya yang disajikan, namun semata karena empati (bahkan mungkin kasihan), karena ruang-ruang pentas seniman senyatanya telah terenggut karena pandemi. Menyaksikan pertunjukan daring lebih sebagai upaya memberi semangat pada seniman agar terus bertahan dibanding penikmatan sepenuhnya pada karya yang disajikan. Oleh karena itu, kita jarang menjumpai komentar seputar kekaryaan yang analitis, dalam, atau bahkan kritis.
Pandemi memungkinkan kesenian menjadi objek bagi eksistensi semu senimannya. Lihatlah salah satunya, Direktorat Jendral Kebudayaan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi program bantuan pada seniman (pertunjukan) terdampak corona dengan salah satu syarat utama melampirkan karya seni yang dibuatnya. Tidak ada mekanisme seberapa jauh karya seni itu dinilai untuk dijadikan pertimbangan penting, tetapi sebatas sebagai syarat administrasi saja agar bantuan dapat diproses.
Karya seni pertunjukan di musim pandemi, new normal, bahkan sesudahnya berpotensi terlepas paling pinggir dalam relung kehidupan manusia yang fobia akan sakit dan kematian. Hal itu seolah menemukan pembenaran, bagaimana mungkin karya seni akan dapat dinikmati secara total dan klimaks jika untuk urusan lain yang dipandang lebih urgen saja masih belum terpenuhi.
Masyarakat masih disibukkan dengan pemulihan segi ekonominya yang terpuruk akibat pandemi. Generasi yang tak memiliki pekerjaan karena dirumahkan secara sepihak dari perusahaan yang tak lagi mampu menggaji. Serta berbagai ketakutan dan pembatasan baru yang akan terjadi sesudah pandemi ke depan.
Mustahil di balik segala persoalan itu publik dapat dengan khusyuk menikmati karya seni sebagaimana dalam situasi normal sebelum pandemi. Tetapi seberapa pun pandemi telah memporakporandakan struktur kehidupan, tidak terkecuali kesenian, ia harus dipandang bukan semata rintangan tetapi juga tantangan. Oleh karena itu mendesak untuk dibuat rumusan tata kelola seni (pertunjukan) ke depan.
Hal-hal yang dapat dipandang penting antara lain bagaimana manajemen penonton, teknik pemanggungan yang aman, serta penataan ruang pementasan yang ramah pada aspek kesehatan. Selama ini aturan yang ada masih bersifat normatif, seperti memakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan, belum mengarah pada hal-hal yang lebih substansial dan tersegmentasi.
Lembaga negara, terkhusus bidang kebudayaan dan kesenian, dapat mengambil peran itu untuk segera menggodok road map bagi nasib hidup seni pertunjukan ke depan. Apabila hal tersebut tidak disegerakan, tidak menutup kemungkinan profesi seniman hanya akan menjadi sejarah masa lalu, karya seni semata menjadi dokumentasi visual dalam linimasa media sosial, dan panggung-panggung pertunjukan menjadi museum atau monumen sekaligus saksi bisu gemuruh perjumpaan indah penonton dengan seniman dan karyanya.
Barangkali kita tidak akan lagi mendengar gaduh suara penonton yang serempak melantunkan lagu di depan penyanyi pujaannya. Kita juga tidak akan bisa berdesakan untuk berjoget di panggung dangdut. Roda perekonomian masyarakat akar rumput lumpuh, tidak ada lagi kumpulan penjual mainan anak, makanan kampung, dan senyum tukang parkir seperti sebelumnya. Semua mungkin terjadi apabila tidak secepatnya diambil tindakan dengan mendaur ulang "ruang berkesenian" hari ini dan ke depan.
Bukankah berkesenian adalah sebentuk upaya menuju kebahagiaan hidup? Tidak ada seni, berarti tidak ada "kehidupan".
Aris Setiawan etnomusikolog, pengajar di ISI Surakarta
(mmu/mmu)